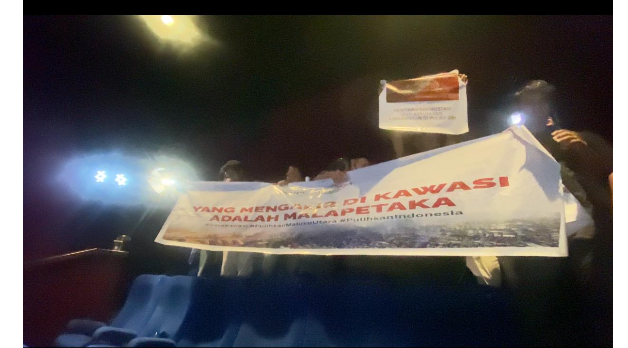“Pembiaran” Kejahatan Korporasi atas kasus KARHUTLA;
Respon atas Arahan Presiden tentang Pengendalian KARHUTLA
Pada tanggal 22 Februari 2021, di Istana Negara Presiden memberikan Arahan tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Melihat perkembangan regulasi dan fakta bagaimana kasus kejahatan korporasi pada kebakaran hutan dan lahan ditangani, kami melihat ini tidak lebih dari lips service, hal ini kami dasarkan atas argumentasi:
Pertama, dalam penanganan kasus Karhutla perintah tanpa kompromi ini sudah dijalankan Polri dengan "baik." Terbukti dari banyaknya penegakan hukum kepada subyek hukum orang-per-orangan. Termasuk masyarakat adat, petani kecil dan lainnya, Silahkan dibandingkan pada statistik Polri dan KLHK, berapa banyak penerapan ketentuan pidana Karhutla antara subjek hukum korporasi dan orang perorangan. Apabila "tanpa kompromi" ini dimaknai dengan penegakan hukum secara pasti dan adil. Ada skema multidoor system. Pertanggungjawaban Karhutla dimintakan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan masuk ke dalam berbagai ruang penegakan hukum, pidana, perdata dan administrasi. Apabila tanpa kompromi, bukan tindakan membakar atau terbakar tapi masuk pada persoalan pokok. Izin konsesi di ekosistem gambut, 2 juta hektar lebih di konsesi HTI dan 4 juta di perkebunan kelapa sawit. Review izinnya berdasarkan ketentuan hukum. Faktanya, larangan aktivitas perizinan di ekosistem gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter sudah berlaku sejak 1990.
Poin selanjutnya, apakah telah maksimal melakukan audit kepatuhannya, seberapa banyak yang patuh melakukan pencegahan dan pemulihan. Terbakar berulang sekalipun sedikit yang izinnya direview. Putusan MA terkait CLS Kalimantan Tengah saja Presidennya masih belum patuh.
Kedua. Pada kesempatan lainnya Presiden mengatakan, 99 persen kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian. Ironisnya dalam arahan Presiden tertanggal 22 februari 2021 lalu, pada point 2 menegaskan “..memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat”, mengesankan problem dominan berada pada perilaku masyarakat.
Faktanya ada andil negara, pengambil kebijakan. Penerbitan izin yang tidak sesuai kriteria serta batasan ekosfer. Salah besar jika hanya menyalahkan manusia plus cuaca. Ini yang disebut era kapitalisme. Legalitas perizinan dijadikan dasar pemaaf penyebab kebakaran. Investasi dan menguntungkan korporasi, bahkan tidak sedikit mengakibatkan konflik. Dampak lain, asap dihadiahkan berulang kepada rakyat.
Ketiga, pada akhirnya kami menilai arahan Presiden menjadi “semu”, bukan lagi pada problem implementasi, pemerintah justru belakangan menerbitkan Omnibus Law CILAKA/ UU Cipta Kerja, yang draft awalnya malah mengakomodir kemauan APHI dan GAPKI dalam uji materil UU PPLH yang dicabut. Walaupun dalam perkembangannya rumusan-rumusan UU Cipta Kerja diperhalus, tapi tetap saja melemahkan pasal 49 UU Kehutanan, Pasal 88 UU PPLH tentang strict liability/pertanggungjawaban mutlak, dan mengendurkan prosedur tindak pidana dengan rumusan-rumusan ketentuan administrasi. Belum lagi cluster perkebunan UU Cipta Kerja yang mempunyai semangat pemutihan keterlanjuran perkebunan di kawasan hutan, alih-alih korporasi yang beroperasi dalam kawasan hutan diberikan sanksi tegas, justru diberikan waktu untuk “menyelesaikan persyaratan” selama 3 tahun (tambahan pasal dari Omnibus Law terhadap UU P3H), padahal data BPK saja menyebut 2,7 juta HA perkebunan sawit berada dalam kawasan hutan secara tidak sah.
Keempat, kami hendak memperlihatkan fakta kebijakan yang sama sekali tidak relevan dengan ucapan Presiden. 24 Oktober 2015 Presiden Jokowi menerbitkan Inpres 11/ 2015. Lalu pada 22 Desember 2015, dimana Sumatera dan Kalimantan masih dalam fase pemulihan, namun kemudian Presiden Jokowi menerbitkan PP 104/ 2015. Ketentuan pasal 51 ayat (1) dan (2) malah melegalkan keterlanjuran perkebunan di kawasan hutan, bahkan di fungsi lindung dan konservasi.
Bahkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, atas nama pangan, justru proyek food estate monokultur skala luas bisa dibuka di hutan fungsi produksi dan lindung, ditambah bonus “fasilitas” tanpa perlu membayar kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH).
Kelima, implementasi penegakan hukum justru berjalan mundur, belum terlihat ada upaya luar biasa Presiden dalam kasus-kasus tersebut, ini berbanding terbalik dengan arahan Presiden tentang Karhutla pada poin 6. Misalnya, masih ada SP3 besar-besaran di Riau pada 2016 di kasus Karhutla. Jika serius pemerintah, mari kita buka pertimbangan Hakim Sorta dan Hakim Isna. SPDP yang tidak ada tanda terimanya berjauhan dan alasan prosedural dengan argumentasi yang tidak jelas menyatakan SP3 sah.
Apalagi jika bicara putusan pemulihan gugatan perdata yang triliyunan tapi belum dilaksanakan. Menang di atas kertas namun tanda tanya dalam eksekusi, bagaimana mungkin melahirkan efek jera?!
Salam Adil dan Lestari
Narahubung
Eksekutif Nasional WALHI
Boy Even Sembiring
085271897255
Wahyu A. Perdana
082112395919